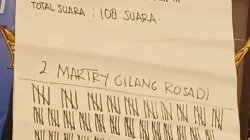JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Retret jilid 2 Kabinet Merah Putih di Hambalang selama sehari penuh kemaren memunculkan perdebatan mengenai arah kepemimpinan pemerintahan nasional.
Di balik simbol disiplin, kekompakan, dan optimisme yang dipertontonkan, muncul pertanyaan mendasar: apakah pendekatan bergaya komando efektif untuk mengelola pemerintahan sipil yang kompleks, majemuk, dan berbasis otonomi daerah?
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dalam percakapan dengan jurnalis menilai retret tersebut lebih mencerminkan glorifikasi kekuasaan ketimbang forum evaluasi kebijakan yang substantif.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, pendekatan yang terlalu militeristik justru berisiko menghambat kualitas pengambilan keputusan.
Kabinet Komando dan Masalah One Way Traffic
Menurut Prof. Djohermansyah, Kabinet Merah Putih saat ini bekerja dalam pola one way traffic—arahan bergerak dari atas ke bawah tanpa ruang dialog yang memadai.
Model ini mungkin efektif untuk konsolidasi cepat, namun lemah dalam menyerap masukan dari pelaksana kebijakan yang memahami persoalan lapangan.
Dalam kabinet yang beranggotakan lebih dari seratus orang, komunikasi dua arah menjadi semakin sulit. Padahal, fungsi kabinet bukan sekadar menerima perintah, melainkan memberi saran, kritik, dan alternatif kebijakan kepada presiden.
Ketika ruang tersebut menyempit, kebijakan berisiko kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial dan administratif.
Retret yang dikemas dengan narasi keberhasilan nyaris sempurna—klaim capaian tinggi tanpa pengakuan sungguh-sungguh atas kelemahan—dinilai tidak sehat dalam tradisi pemerintahan demokratis. Kritik, menurutnya, bukan ancaman, melainkan vitamin bagi kebijakan publik.
Pemerintahan Bukan Sekadar Penguasa
Prof. Djohermansyah menekankan bahwa pemerintahan modern tidak identik dengan presiden dan kabinet semata.
Pemerintahan adalah ekosistem yang melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, komunitas lokal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ketika pemerintah tampil seolah menjadi satu-satunya aktor pembangunan, partisipasi publik akan melemah.
Akibatnya, legitimasi kebijakan menurun dan dukungan sosial menyempit.
Dalam jangka panjang, hal ini justru memperlambat pencapaian tujuan negara.
Kabinet Gemuk dan Beban Koordinasi
Struktur kabinet yang sangat besar dinilai menambah persoalan birokrasi.
Semakin banyak kementerian dan lembaga, semakin rumit koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan—terutama dengan pemerintah daerah.
Relasi pusat-daerah menjadi semakin berat karena daerah harus berhadapan dengan terlalu banyak “atasan” di Jakarta.
Kondisi ini berpotensi memperparah tumpang tindih kebijakan dan memperlambat eksekusi program.
Prof. Djohermansyah mendorong agar struktur kabinet dievaluasi secara serius setelah satu tahun berjalan.
Kementerian atau lembaga yang terbukti tidak efektif seharusnya digabung atau dihapus, bukan dipertahankan demi kompromi politik.
Disiplin Komando versus Otonomi Daerah
Pendekatan disiplin ala militer dinilai tidak sepenuhnya kompatibel dengan realitas otonomi daerah.
Indonesia adalah negara yang sangat beragam—secara geografis, sosial, budaya, dan ekonomi.
Dalam konteks ini, kepemimpinan yang terlalu sentralistik berisiko mematikan kreativitas dan inovasi daerah.
Model komando cenderung menciptakan aparatur yang patuh tetapi pasif. Inisiatif terhambat, kritik dibungkam, dan keputusan hanya lahir dari lingkaran kekuasaan terbatas.
Padahal, banyak solusi kebijakan justru berasal dari aktor daerah yang memahami kondisi riil di lapangan.
Selain itu, pemotongan dana transfer ke daerah dan penguatan kembali sentralisme fiskal berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.
Retret atau Sekadar Rapat Evaluasi?
Prof. Djohermansyah menilai istilah “retret” dalam konteks ini membingungkan.
Kegiatan tersebut pada dasarnya adalah rapat evaluasi satu hari, bukan retret dalam pengertian pembekalan intensif atau refleksi mendalam.
Penggunaan istilah dan simbol-simbol militer justru menciptakan persepsi keliru tentang arah pemerintahan.
Dalam praktik pemerintahan sipil, mekanisme evaluasi sudah jelas: rapat kabinet paripurna, rapat terbatas, dan rapat evaluasi berkala. Tidak diperlukan istilah baru yang menimbulkan kebingungan publik.
Tata ruang rapat yang klassikal—ala guru dan murid—juga mempertegas watak komando, bukan kolektif kolegial. Padahal, kabinet seharusnya menjadi ruang deliberasi, bukan sekadar forum mendengar arahan.
Kebijakan Pusat dan Keberagaman Daerah
Kepada para menteri, Prof. Djohermansyah mengingatkan agar hindari kebijakan pusat-sentris dan pendekatan “one policy fit for all”.
Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda—kepulauan, pegunungan, perkotaan, hingga wilayah tertinggal.
Kebijakan nasional harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dan kepala daerah seyogianya diposisikan sebagai mitra, bukan bawahan. Menteri adalah pejabat yang diangkat presiden, sementara kepala daerah adalah pejabat yang dipilih rakyat.
Relasi keduanya bersifat sejajar dalam kerangka demokrasi.
Ketika kepala daerah hanya dijadikan penonton, program nasional berisiko gagal di tingkat implementasi. Yang terjadi bukan pembangunan daerah, melainkan sekadar pembangunan di daerah.
Retret Kabinet Hambalang, dalam pandangan Prof. Djohermansyah Djohan, belum menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan.
Disiplin tanpa dialog, struktur gemuk tanpa evaluasi, serta sentralisme tanpa sensitivitas daerah justru berpotensi melemahkan kinerja negara.
Tanpa koreksi mendasar, simbol kekompakan hanya akan menjadi seremoni tahunan—bukan instrumen perbaikan kebijakan.
Pemerintahan yang kuat bukanlah yang paling patuh pada komando, melainkan yang paling terbuka pada kritik dan paling mampu bekerja bersama seluruh elemen bangsa. (rls)