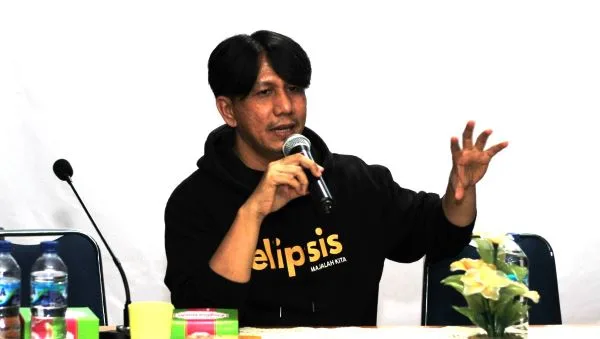Oleh : Muhammad Subhan*)
PENGURUS Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP/MTs Kota Padang Panjang mengundang saya untuk memberikan workshop literasi sekaligus menghadiri penyerahan hadiah Lomba Cipta Cerpen dan Baca Puisi Tingkat SMP/MTs se-Kota Padang Panjang, Selasa, 11 November 2025, di aula SMP Negeri 4 Padang Panjang.
Sebagai juri, karya peserta secara daring telah saya seleksi sejak dua pekan sebelumnya, termasuk ketika saya sedang berada di Jakarta mendampingi salah satu siswi Padang Panjang yang mengikuti puncak Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tingkat Nasional 2025.
Kemarin, para pemenang lomba diumumkan. Saya ikut menyerahkan hadiah dan menyaksikan wajah-wajah yang penuh semangat. Ada kebahagiaan tersendiri melihat bibit-bibit penulis dan pembaca puisi muda Padang Panjang itu.
Namun, kebahagiaan itu sekaligus mengundang kegelisahan: setelah lomba usai, ke mana anak-anak ini akan berlatih lagi? Bagaimana talenta mereka dijaga agar tidak padam dan dapat terus melahirkan karya?
Menulis cerpen, menulis puisi, atau membaca puisi bukanlah bakat yang tumbuh sekali jadi. Ia memerlukan latihan panjang, bimbingan yang tekun, dan ruang yang mendukung.
Karena itu, dalam workshop saya sampaikan, sekolah sudah semestinya memberikan ruang yang lebih besar bagi kegiatan literasi. Wadahnya bisa berupa sanggar sastra siswa. Sanggar ini harus dibentuk dan dijaga. Tempat di mana anak-anak berlatih menulis, berdiskusi, membaca, dan membedah karya dengan suasana menyenangkan. Iklim itu diciptakan terus-menerus.
Sayangnya, di banyak sekolah, di mana pun, kegiatan sastra masih dipandang “sebelah mata”. Saat lomba tiba, barulah guru kebingungan mencari wakil sekolah, “mencomot” siapa saja yang “terlihat berbakat”, padahal mereka tidak pernah diberi ruang pembinaan sebelumnya. Kalaupun ada, porsi latihannya sangat sedikit sekali.
Sanggar sastra di sekolah seharusnya disejajarkan dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti Pramuka, Tahfiz, PMR, Seni Tari, Teater, Musik, dan lainnya. Ia tidak boleh menjadi kegiatan musiman, apalagi sekadar formalitas saat ada lomba.
Bila dilakukan rutin, misalnya sepekan sekali, sanggar sastra dapat menjadi ruang kreatif yang menghidupkan imajinasi siswa.
Setiap pekan, siswa dapat menulis puisi atau cerpen, lalu membacakan karyanya di depan teman-teman. Guru memfasilitasi dengan memberikan bacaan bermutu. Bacaan bermutu itu buku-buku karya penulis maestro, cerpen-cerpen pilihan, dan antologi puisi terbaik.
Di sesi bedah karya, guru dan siswa bersama-sama mendiskusikan isi dan gaya penulisan. Kupas tuntas kelebihan dan kekurangannya. Dari kegiatan ini akan terbangun budaya apresiasi dan kritik. Lebih lanjut, siswa belajar menulis dengan kesadaran, bukan sekadar meniru.
Setelah itu, karya yang dianggap baik bisa diarahkan untuk dikirim ke berbagai kompetisi menulis pelajar atau dimuat di media massa. Pada tahap akhir, hasil tulisan siswa dapat diterbitkan dalam bentuk buku antologi sekolah, baik berupa kumpulan cerpen, puisi, atau esai reflektif.
Buku itu tidak sekadar terbit, bikin acara peluncurannya, kemudian dibedah lagi. Terbitkan lagi. Terus begitu.
Dengan cara ini, sekolah tidak hanya melahirkan penulis, tapi juga menanamkan kebanggaan literasi kepada seluruh warganya.
Namun, semua itu tidak akan berjalan bila tidak ada “pilot pengemudi” gerakan literasi, yakni kepala sekolah. Kepala sekolah harus berdiri di garda terdepan, menjadi motor penggerak utama. Ia harus memahami bahwa literasi bukan tambahan kegiatan, bukan sekadar tanggung jawab guru bidang studi Bahasa Indonesia, tetapi fondasi pembentukan karakter dan budaya belajar. Kerjanya harus kolektif dan kolaboratif.
Kepala sekolah perlu membentuk tim literasi sekolah yang solid, terdiri dari guru-guru Bahasa Indonesia, pustakawan, guru seni budaya, guru-guru bidang studi lainnya yang tertarik literasi, dan wali kelas, yang bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk merancang kegiatan literasi terencana.
Gerakan literasi dapat disinergikan dengan berbagai program sekolah, misalnya Adiwiyata. Kegiatan menulis dapat dikaitkan dengan tema lingkungan: menulis puisi tentang alam, membuat esai tentang kebersihan sekolah, atau menciptakan cerpen bertema kelestarian bumi. Dengan begitu, literasi tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kepedulian sosial.
Selain itu, sekolah perlu menyediakan waktu khusus untuk kegiatan literasi, misalnya satu jam setiap minggu untuk membaca dan menulis kreatif. Waktu ini jangan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk berlatih menulis, berdiskusi, dan menumbuhkan daya pikir kritis.
Bila memungkinkan, libatkan praktisi atau penulis profesional dari luar sekolah agar siswa dan guru mendapat inspirasi segar.
Gerakan literasi tidak akan hidup jika hanya diserahkan pada guru Bahasa Indonesia. Ia harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen sekolah. Guru IPA bisa mengajak siswa menulis laporan ilmiah populer, guru IPS mengarahkan siswa membuat catatan perjalanan lapangan, sementara guru seni membimbing mereka menulis kritik atau ulasan karya.
Semakin lintas disiplin, semakin luas pula daya jangkau literasi itu.
Sastra—sebagai bagian dari literasi—harus diajarkan dengan cara yang asyik dan menyenangkan. Tidak melulu berbicara teori majas atau unsur intrinsik, tetapi lebih banyak praktik kreatif: menulis bebas, membuat video pembacaan puisi atau pembacaan cerpen, atau pentas monolog yang naskahnya berangkat dari karya sastra.
Suasana yang cair dan hangat dalam proses belajar itu akan membuat siswa lebih berani berekspresi, lebih percaya diri, dan menemukan dirinya di dalam kata.
Kita hidup di zaman digital, di mana perhatian anak-anak mudah terpecah oleh gawai dan media sosial. Karena itu, sastra di sekolah perlu dikemas dengan pendekatan baru yang relevan dengan kehidupan mereka.
Cerpen bisa diunggah di website literasi sekolah, puisi bisa dibacakan di kanal YouTube, TikTok, Facebook, Instagram milik sekolah, dan hasil karya siswa itu dibagikan kembali melalui media sosial pribadi masing-masing sebagai bentuk perluasan informasi dan publikasi. Guru juga ikut membagikannya.
Dengan begitu, sastra tidak terpinggirkan, tetapi hadir dalam ruang yang akrab bagi siswa.
Sastra bukan pelajaran tambahan, melainkan jalan membangun empati, imajinasi, dan kepekaan sosial. Sekolah yang memiliki sanggar sastra akan melahirkan generasi pembelajar yang berpikir kritis, menulis dengan hati, dan membaca dengan rasa.
Itulah makna sejati dari literasi: melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga halus budinya. Pintu masuknya lewat menulis kreatif, khususnya sastra, sekaligus diberi ruang apresiasi yang terus-menerus agar makin bertumbuh dan berkembang. []
Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, dan founder Sekolah Menulis elipsis.*)