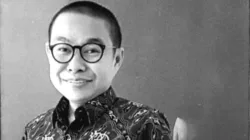Oleh : Prof. Herri*)
Naik ke Puncak Lawang menatap awan,
Tampak Danau Maninjau berkilau tenang.
UMKM tumbuh bila saling sandaran,
Yang besar menuntun, yang kecil pun gemilang.
Pantun ini menggambarkan filosofi dasar ekonomi Sumatera Barat —kebersamaan dan saling menguatkan. Di balik semangat berdagang, berkarya, dan berinovasi masyarakat Minang, terdapat nilai gotong royong dan kemandirian yang telah lama mengakar.
Semangat inilah yang menjadi roh penggerak UMKM di ranah Minang.
Namun untuk menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi berkelanjutan, diperlukan transformasi yang terarah: dari bertahan menjadi tumbuh, dari tradisi menuju inovasi, dari lokal ke global.
Pondasi Ekonomi Rakyat yang Belum Tergarap Maksimal
UMKM merupakan urat nadi perekonomian Sumatera Barat. Hampir di setiap nagari, di setiap sudut pasar tradisional, kita dapat menemukan aktivitas ekonomi kecil yang hidup, menjadi penggerak keseharian masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, terdapat sekitar 593.100 unit usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lebih dari 553 ribu di antaranya merupakan usaha mikro. Artinya, lebih dari 93 persen pelaku usaha di provinsi ini masih berada pada skala yang sangat kecil, dengan modal terbatas dan pasar yang relatif sempit.
Rasio kewirausahaan Sumatera Barat yang mencapai 4,10 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (3,04 persen), menunjukkan semangat berusaha masyarakat Minang yang kuat. Tradisi merantau dan kemandirian ekonomi menjadi modal sosial berharga.
Namun, semangat ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam produktivitas dan daya saing yang tinggi. Sebagian besar UMKM masih berorientasi pada survival economy — usaha untuk memenuhi kebutuhan harian, belum berorientasi pada pertumbuhan strategis.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen. Target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sumatera Barat 2025 mencapai Rp 8,3 triliun, naik 4,65 persen dari tahun sebelumnya. Hingga triwulan I tahun ini, realisasi mencapai Rp 1,969 triliun (23,7 persen), dengan sektor pertanian sebagai penerima terbesar (44,55 persen). Ini menegaskan dominasi kegiatan ekonomi berbasis pertanian dan olahan hasil bumi di Sumbar.
Namun di balik data yang menjanjikan, terdapat tantangan mendasar. Kesadaran hukum dan perlindungan usaha masih rendah. Hingga akhir 2024, hanya 297 pelaku UMKM di Sumbar yang mendaftarkan merek dagangnya, suatu jumlah yang sangat kecil dibanding total pelaku usaha. Padahal merek merupakan aset tak berwujud yang menentukan nilai dan daya tawar produk.
Sementara itu, digitalisasi memang mulai tumbuh: lebih dari 50.000 pelaku usaha telah memanfaatkan platform fintech dan marketplace. Namun, jumlah itu baru sekitar 8 persen dari total UMKM. Ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi digital Sumatera Barat masih sangat luas, tetapi belum tergarap optimal.
Tantangan Struktural: Antara Tradisi dan Transformasi
Karakteristik UMKM di Sumatera Barat sangat khas. Banyak usaha lahir dari tradisi kerajinan, kuliner, dan jasa rumahan yang diwariskan turun-temurun. Model keluarga ini menjadi kekuatan sosial, tetapi juga membatasi ekspansi usaha, karena sering kali tidak ada pemisahan antara urusan rumah tangga dan bisnis.
Sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal, tanpa legalitas usaha dan pembukuan yang tertib. Akibatnya, mereka sulit mengakses pembiayaan formal dan program kemitraan. Rendahnya literasi keuangan membuat banyak pelaku usaha tidak memiliki rencana bisnis jangka panjang, tidak memahami manajemen risiko, dan sulit meningkatkan kapasitas produksi.
Kerentanan terhadap bencana alam juga menjadi tantangan nyata. Gempa Pasaman Barat tahun 2022 berdampak pada lebih dari 400 UMKM dengan kerugian sekitar Rp 8 miliar. Di Bukittinggi, kebakaran pasar beberapa kali melumpuhkan pedagang kecil yang tak memiliki perlindungan asuransi. Budaya menghitung risiko dan merancang keberlanjutan belum menjadi kebiasaan.
Karena itu, pembinaan UMKM tidak bisa lagi sebatas pelatihan teknis atau bantuan modal. Diperlukan perubahan cara berpikir dan cara mengelola usaha, yang dari sekadar bertahan menjadi bertumbuh, dari reaktif menjadi strategis, dan dari informal menuju profesional.
Pembinaan Berbasis Klaster: Dari Seragam ke Spesifik
Pendekatan pembinaan UMKM harus bergeser dari massal menjadi berbasis klaster. Ini artinya, pembinaan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kapasitas pelaku usaha.
Lima aspek utama klasterisasi adalah lingkup pasar, kekuatan modal, tingkat teknologi, kualitas SDM, dan prospek usaha.
Pertama, lingkup pasar: UMKM lokal perlu didukung dalam penguatan kualitas produk, desain kemasan, dan akses pasar digital. Sementara yang sudah menembus pasar nasional atau ekspor perlu bimbingan dalam sertifikasi, branding global, dan rantai pasok.
Kedua, kekuatan modal, sebagian besar UMKM masih padat karya. Pembinaan diarahkan pada literasi keuangan, pencatatan usaha, dan manajemen arus kas agar modal kerja dapat dikelola efisien dan berkelanjutan.
Ketiga, teknologi, kesenjangan antara pelaku usaha manual dan digital perlu dijembatani. Program pendampingan harus memperkenalkan teknologi tepat guna, e-commerce, dan bahkan AI sederhana untuk promosi dan pemasaran.
Keempat, kualitas SDM, pelatihan harus menyentuh kepemimpinan usaha, komunikasi, inovasi, dan pemahaman tren pasar. UMKM menengah ke atas bisa diarahkan pada jejaring bisnis, investasi bersama, dan strategi ekspor.
Kelima, prospek usaha, fokus pada sektor-sektor berpeluang tinggi seperti olahan pangan lokal, industri kreatif, busana etnik, dan pariwisata berbasis budaya.
Dengan pendekatan klaster, pembinaan menjadi lebih presisi dan berdampak. UMKM pemula mendapat fondasi untuk bertahan, yang mapan mendapat dorongan untuk naik kelas.
Kemitraan Strategis dan Ekosistem Investasi
UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Mereka membutuhkan kemitraan strategis dengan perusahaan besar, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Usaha besar dapat berperan sebagai anchor company yang memberikan transfer teknologi dan standar mutu kepada pemasok kecil.
Pola seperti ini sukses di Jepang dengan sistem Kyōryokukai, di mana hubungan jangka panjang antara usaha besar dan kecil saling memperkuat.
Namun, kemitraan hanya efektif jika ada iklim investasi yang sehat. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, kebijakan yang konsisten, dan birokrasi yang efisien. Ketidakpastian regulasi sering membuat investor enggan menanamkan modal. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem berusaha: infrastruktur dasar (jalan, listrik, air, internet), penyederhanaan perizinan, dan digitalisasi layanan publik.
Potensi investasi di Sumatera Barat sangat besar, seperti pangan, pariwisata, energi terbarukan, dan industri halal. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, maka bukan hanya investasi yang tumbuh, tetapi juga rantai nilai ekonomi yang melibatkan ribuan UMKM di seluruh daerah.
Menuju Ekonomi Berkelanjutan: Yang Besar Mengangkat yang Kecil
Dengan lebih dari 593 ribu pelaku usaha, rasio wirausaha 4,10 persen, dan digitalisasi yang mulai tumbuh, Sumatera Barat sesungguhnya telah memiliki pondasi kuat menuju ekonomi berkelanjutan. Namun keberhasilan sejati tidak diukur dari banyaknya jumlah UMKM, melainkan dari berapa banyak yang mampu naik kelas dan bertahan menghadapi perubahan zaman.
Ekonomi berkelanjutan menuntut sinergi antara semua pelaku: pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah menjadi fasilitator, bukan sekadar pemberi bantuan. Dunia usaha membuka ruang kolaborasi, bukan kompetisi yang menyingkirkan yang kecil. Dan UMKM sendiri harus terus belajar, beradaptasi, serta menumbuhkan kepercayaan diri menembus pasar yang lebih luas.
Karena sesungguhnya, untuk maju kita memang perlu yang besar, tetapi yang besar harus mampu mengangkat yang kecil, agar tumbuh dan berdaya bersama. Itulah filosofi Minang yang sejati: “Basamo mako manjadi. []
Ketua Program Doktor Manajemen FEB Unand*)